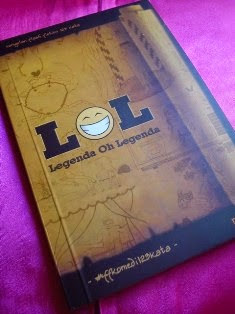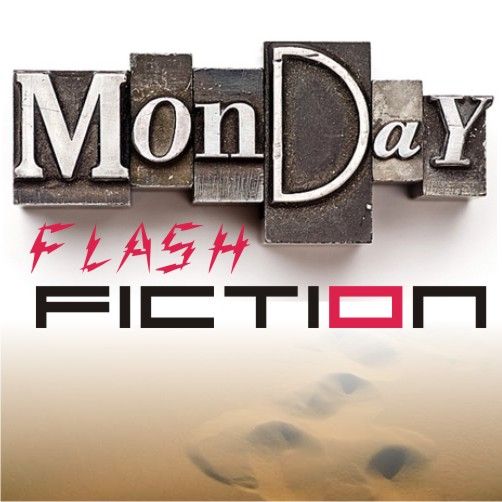Judul : Katarsis
Genre : Psychology Thriller
Penulis :Anastasia Aemilia
Editor : Hetih Rusli
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Cetakan : Pertama, April 2013
Tebal : 264 halaman
ISBN : 978-979-22-9466-8
Blurb:
Tara Johandi, gadis berusia delapan belas tahun, menjadi satu-satunya saksi dalam perampokan tragis di rumah pamannya di Bandung. Ketika ditemukan dia disekap di dalam kotak perkakas kayu dalam kondisi syok berat. Polisi menduga pelakunya sepasang perampok yang sudah lama menjadi buronan. Tapi selama penyelidikan, satu demi satu petunjuk mulai menunjukkan keganjilan.
Sebagai psikiater, Alfons berusaha membantu Tara lepas dari traumanya. Meski dia tahu itu tidak mudah. Ada sesuatu dalam masa lalu Tara yang disembunyikan gadis itu dengan sangat rapat. Namun, sebelum hal itu terpecahkan, muncul Ello, pria teman masa kecil Tara yang mengusik usaha Alfons.
Dan bersamaan dengan kemunculan Ello, polisi dihadapkan dengan kasus pembunuhan berantai yang melibatkan kotak perkakas kayu seperti yang dipakai untuk menyekap Tara. Apakah Tara sesungguhnya hanya korban atau dia menyembunyikan jejak masa lalu yang kelam?
Review:
Katarsis -- Upaya "pembersihan" atau "penyucian" diri, pembaruan rohani dan pelepasan diri dari ketegangan. (Wikipedia)
Mencekam! Untuk pembaca yang tidak terbiasa membaca kisah-kisah thriller, mungkin akan mengernyitkan kening berkali-kali, nggak nafsu minum, atau malah menutup buku sebelum menyelesaikannya. Karena kisah di dalam novel ini bukan sekadar pembunuhan. Lebih dari itu. Bahkan tokohnya merasakan kepuasan saat melakukannya. Sakit!
Bisa dibilang aku sudah terbiasa membaca kisah-kisah thriller (membaca ya, bukan pelakunya, hehe). Aku tergabung dengan komunitas MFF (Monday Flash Fiction), sebuah komunitas menulis FF, di mana terkadang prompt mingguannya, menantang member untuk menuliskan sebuah FF bergenre thriller. Bahkan ketika tantangan prompt membebaskan member untuk menulis genre apapun, beberapa member tetap menulis FF bergenre thriller. Jadi aku sudah cukup familier dengan kisah-kisah sadis semacam ini. Dan novel ini memuaskanku sebagai pembaca.
Aku suka covernya. Cukup menggambarkan bagaimana 'sakit'-nya Tara. Ia adalah seorang anak yang membenci namanya sendiri, keluarganya sendiri, dan perlakuan-perlakuan untuknya.
Aku bukan Tara. Itu yang selalu kukatakan pada mereka sejak aku belajar bicara. Bahkan sejak keluar dari rahim Tari pun aku selalu ingin meneriakkan kalimat itu pada mereka. -- hal. 29
Tak dijelaskan mengapa Tara begitu membenci semua di sekitarnya, bahkan semenjak ia masih sangat kecil. Jadi aku sempat mengira bahwa ada semacam setan yang merasuki jiwa Tara, menggunakan raganya, dan bersemayam di sana selamanya, hehe. Atau mungkin memang ada jenis penyakit jiwa yang terbawa semenjak lahir?
Ketika bertamasya di taman, Tara terjatuh dari sepeda. Seorang anak laki-laki bernama Ello menolongnya dan memberikan koin lima rupiah. Tara menganggapnya konyol, namun mempercayainya, bahkan sampai mengalami ketergantungan terhadap koin tersebut. Ia percaya, rasa sakit dalam bentuk apapun yang dirasakannya akan surut jika ia menggenggamnya.
"Ini, pegang. Mamaku bilang, kalau lagi sakit, kita harus pegang koin biar sakitnya berkurang." -- hal. 39
(Mereka ini baru sekali bertemu, jadi aku kurang setuju kalau di dalam blurb, Ello disebut sebagai teman masa kecil Tarra. Karena setelah itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Baru bertemu saat mereka dewasa.)
Suatu hari, kejadian buruk menimpa Tara. Seseorang memperkosanya, dan itu mendorongnya
untuk melakukan sesuatu di luar batas. Ia membunuh dan memutilasi
pelakunya. Apa yang ia lakukan, menjadi penyebab kekacauan di
keluarganya, dan membuatnya terkurung di kotak perkakas kayu hingga
hampir mati. Aroma mint yang tercium ketika ia terkurung menjadikan trauma untuknya.
Tara berhasil ditemukan, tapi kisah tidak lantas selesai begitu saja. Terjadi pembunuhan berantai dengan kotak perkakas kayu sebagai tempat mayat diletakkan dan koin 5 rupiah di dalam kotak tersebut. Tidak ada motif jelas yang menghubungkan korban satu dan lainnya, sehingga ini menyulitkan polisi.
Jadi, ada tiga hal yang menjadi keyword dalam kisah ini, yaitu: kotak perkakas kayu, aroma mint, dan koin 5 rupiah.
***
Ditulis
dengan POV pertama, bergantian antara Tara dan Ello, membuatku harus
berpikir sedikit lebih keras untuk menebak, ini bagian siapa, ya. Tapi
itu bukan masalah besar, karena penulis menebusnya dengan diksi yang
sangat apik. Ia canggih dalam memilih kata. Tulisannya padat. Caranya
membagi novel ini menjadi 66 bab + prolog dan epilog, juga patut
diacungi jempol. Tulisan di tiap babnya singkat, tetapi tetap mengena
dan membuat penasaran. Sehingga sebagai pembaca, aku tidak merasakan
kejenuhan sedikit pun. Bahkan tidak ingin melepaskan novel ini sampai selesai.
Quote favorit:
- Kewarasan divonis tanpa menggunakan stetoskop, termometer, atau rontgen. Buatku itu sama sekali tidak masuk akal. -- hal. 51
- Kurasa benar kata orang, berhati-hatilah dengan apa yang kau harapkan, kau takkan tahu bagaimana permohonanmu akan dikabulkan. -- hal 108
- Rasa sakit itu ada untuk melindungi dan mengajarimu banyak hal. -- hal. 183
Aku berikan 4 bintang dari 5 bintang yang aku punya.
Ayo Kak Anastasia, tulis lagi dong buku bergenre serupa dan yang lebih seru dari ini. Atau kisah lanjutan dari kehidupan Tara juga boleh :D