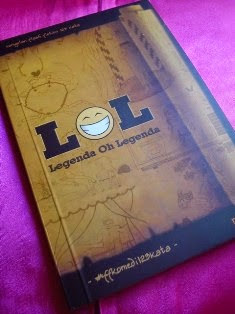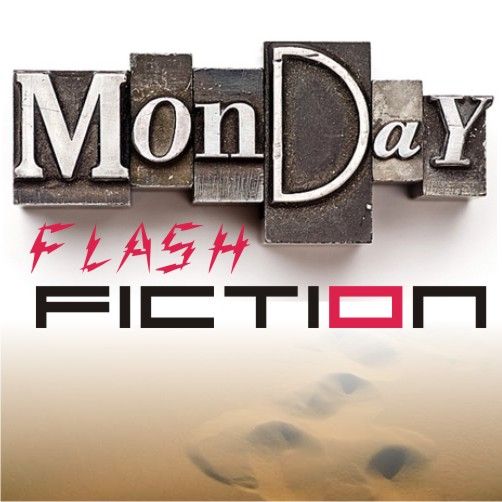Kreatifitas tak pernah mati. Bahkan ketika orang itu mati, kreatifitas akan terus hidup dalam karyanya. Walaupun nantinya banyak tokoh pengganti yang bermunculan.
Home » Archives for July 2013
Kenangan
Seperti goresan pensil yang tetap menyisakan tulisan samar ketika penghapus sudah berusaha menghapusnya sedemikian rupa. Begitulah masa lalu yang tetap menyisakan ingatan walau kita telah bersusah payah melupakannya. Hal yang normal ini bernama kenangan.
Parcel Terakhir (Sepertinya)
“Ngapain sih sayang, kok nongkrong di ruang tamu tiap hari?”
“Nggak tiap hari juga kali ma. Baru 4 hari ini kan. Nungguin
kurir antar parcel nih. Mama kayak nggak tahu aja.”
Beginilah kebiasaanku beberapa hari menjelang Lebaran. Menunggu
kurir yang mengantarkan parcel
bertuliskan: Selamat Hari Raya Idul Fitri dari Rendra – mantan kekasihku.
Sudah 6 tahun ini aku dan Rendra saling berkirim parcel
seperti itu menjelang Lebaran. Kebiasaan semenjak kami pacaran. Meskipun kami
sudah tidak lagi menjadi sepasang kekasih sejak 3 tahun yang lalu, tetapi
kebiasaan ini tidak hilang begitu saja. Menjaga silaturahmi, begitu kata
Rendra.
Aku menurut saja. Lagipula aku senang melakukannya. Dengan
begini, aku masih bisa berharap hubungan kami terjalin seperti dulu. Merangkai
mimpi bersama dan menjalani hari-hari bersama.
Ternyata hari ini kurir yang aku tunggu belum juga datang.
Tak apa-apa. Besok aku tunggu lagi.
”Ada bingkisan untuk Mbak Nurul,” ujar kurir itu sambil
memperlihatkan struk berisi nama lengkap dan alamatku. Ini dia! Akhirnya datang
juga.
“Oh iya benar. Saya sendiri.” Aku menerima parcel itu dengan
hati yang melonjak gembira. Setelah menandatangani struk dan mengucapkan terima
kasih pada kurir, parcel itu aku bawa masuk ke dalam rumah.
Parcel itu terhitung paling besar dibanding tahun-tahun
sebelumnya. Berisi coklat beragam bentuk dan kemasan. Berbeda dengan tahun
sebelumnya yang berisi kue kering atau makanan ringan kemasan khas Lebaran.
Selain isi parcel yang berbeda dari biasanya, ada sesuatu
yang lain yang mencuri perhatianku. Amplop pink yang dilekatkan pada plastik
bening yang membungkus parcel pada bagian depan. Aku segera membukanya. Tidak
sabar sekali mengetahui kata-kata apa yang Rendra susun untukku.
“Kenapa begini Rendra?”
Helaan nafasku berat sekali saat membaca isi dari amplop pink tersebut yang
ternyata adalah undangan pernikahanmu.
Rendra Yudhistira dan Dian Purnamasari.
Akankah ini menjadi parcel terakhir
darimu untukku?
Jangan Salahkan Matahari!
Sinar matahari menyentak kulit.
Melelehkan peluh yang semakin
membanjir.
Bara semangat tak lagi menyala.
Pupus menjadi arang yang teronggok.
Bukan. Bukan menyalahkan matahari.
Diri saja yang tak kuat.
Kesempatan hilang seiring lemahnya
kemauan.
Memberi celah untuk siapa pun yang
lebih kuat.
Berdiri!
Siapa suruh menangisi hari.
Cuaca adalah karunia.
Bergabunglah dengan panas dan ciptakan nyala yang lebih dahsyat.
Bergabunglah dengan panas dan ciptakan nyala yang lebih dahsyat.
Melampiaskan Kekesalan
"Anjing! Di saat
kayak gini, printer malah nggak bisa dipakai.” Beni menggebrak printer di
hadapannya. Ia sangat kesal dengan benda itu. Di saat harus segera mencetak
bagian skripsinya, printer itu malah ngadat dan tidak bisa mengeluarkan tinta.
Padahal jelas-jelas tintanya baru saja diisi ulang.
Salah Beni juga sebenarnya. Mengapa bangun kesiangan. Sudah tahu janjian pukul 10 pagi dengan dosen pembimbing. Tapi baru bangun pukul 9. Itupun belum mencetak hasil revisi skripsi yang sudah ia kerjakan semalam.
Sudah tahu dosen pembimbingnya itu sangat on time. Tiada ampun untuk mahasiswa yang melanggar waktu perjanjian. Bimbingannya akan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai dosen tersebut benar-benar hilang kekesalannya.
Tania yang baru datang terdiam cukup lama di depan pintu kamar kos Beni. Suara benda-benda yang dibanting membuatnya tercengang dan menimbang-nimbang apakah akan masuk ke dalam atau tidak.
Tania memutuskan masuk. Ia mendapati Beni yang dengan tampang masih berantakan sedang duduk mengutak-atik printer. Wajahnya menyeramkan. Seperti tertulis “Jangan ganggu aku!” di jidatnya.
“Makan dulu Ben. Aku bawain ketoprak nih. Tadi beli di tempat biasa. Sarapan bareng yuk,” ajak Tania lembut.
Beni diam saja. Ia masih sibuk dengan printer ngadatnya. Sesekali menggebrak printer itu.
Memangnya printer akan beres begitu digebrak. Malah tambah rusak, iya. Begitu pikir Tania. Ia kemudian menghampiri Beni. Menarik lengannya. Bermaksud mengajaknya sarapan dulu.
“Sebentar! Nggak lihat apa aku lagi ngapain?!” bentak Beni pada Tania. Dihempaskannya tangan Tania dengan kasar.
Tania pergi begitu saja meninggalkan Beni.
Salah Beni juga sebenarnya. Mengapa bangun kesiangan. Sudah tahu janjian pukul 10 pagi dengan dosen pembimbing. Tapi baru bangun pukul 9. Itupun belum mencetak hasil revisi skripsi yang sudah ia kerjakan semalam.
Sudah tahu dosen pembimbingnya itu sangat on time. Tiada ampun untuk mahasiswa yang melanggar waktu perjanjian. Bimbingannya akan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai dosen tersebut benar-benar hilang kekesalannya.
Tania yang baru datang terdiam cukup lama di depan pintu kamar kos Beni. Suara benda-benda yang dibanting membuatnya tercengang dan menimbang-nimbang apakah akan masuk ke dalam atau tidak.
Tania memutuskan masuk. Ia mendapati Beni yang dengan tampang masih berantakan sedang duduk mengutak-atik printer. Wajahnya menyeramkan. Seperti tertulis “Jangan ganggu aku!” di jidatnya.
“Makan dulu Ben. Aku bawain ketoprak nih. Tadi beli di tempat biasa. Sarapan bareng yuk,” ajak Tania lembut.
Beni diam saja. Ia masih sibuk dengan printer ngadatnya. Sesekali menggebrak printer itu.
Memangnya printer akan beres begitu digebrak. Malah tambah rusak, iya. Begitu pikir Tania. Ia kemudian menghampiri Beni. Menarik lengannya. Bermaksud mengajaknya sarapan dulu.
“Sebentar! Nggak lihat apa aku lagi ngapain?!” bentak Beni pada Tania. Dihempaskannya tangan Tania dengan kasar.
Tania pergi begitu saja meninggalkan Beni.
***
“Kok diem?”
“Nggak boleh?”
“Maaf deh tadi aku sempet bentak kamu. Soalnya keadaannya lagi darurat banget. Revisian skripsi itu harus segera aku cetak. Sedangkan printernya tiba-tiba ngadat. Padahal aku harus ketemu dosen saat itu juga. Aku bangun kesiangan.”
“Salahku kalau printernya ngadat? Salahku juga kalau kamu bangun kesiangan?”
“Ya bukan. Udahlah sayang, jangan ngambek terus ya,” bujuk Beni lembut.
“Udahlah sayang... Kita udahan aja ya,” jawab Tania menirukan nada bicara Beni.
“Kenapa?”
“Kenapa? Harusnya aku yang tanya kenapa. Kenapa kamu selalu melampiaskan kekesalan sama apa yang lagi ada di dekatmu?”
“Maksudnya?”
“Jadi kamu nggak sadar? Inget nggak, uda berapa kali kamu bentak aku ketika sesuatu yang kamu hadapi sedang berjalan tidak sebagaimana mestinya? Bersikaplah sedikit lebih bijak. Manusia saja pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana dengan barang yang jelas-jelas buatan manusia. Rusak adalah hal biasa. Kamu harus memakluminya. Jangan hanya menyuruh orang lain maklum ketika kamu sedang marah-marah!”
“Tapi kan....” belum sempat Beni menyelesaikan kalimatnya.
“Tapi kan aku uda nggak sanggup jadi tempatmu melampiaskan kemarahan. Beri tahu aku kalau kamu sudah berhasil menetralkan emosimu di saat terdesak. Saat itu mungkin aku bisa berpikir ulang apakah akan kembali padamu atau tidak.”
Tania berjalan meninggalkan Beni.
Ngabuburit Rutin
Bola itu bergulir, berpindah dari kaki satu ke kaki yang
lain. Terkadang seorang anak laki-laki yang tampaknya kapten tim itu ribut
sekali ketika temannya tidak bisa menerima operan bola darinya, sehingga
membuat bola berpindah ke kaki lawan.
Aku tersenyum melihat kelincahan mereka memainkan bola.
Sesekali aku tertawa geli ketika kapten berteriak kesal jika temannya gagal
menciptakan gol. Lapangan menjadi ramai dengan adanya mereka.
Mengatur teman-teman sekaligus mengatur pola serangan adalah
keahlianku. Aku adalah kapten seperti anak di tengah lapangan itu. Tapi itu
dulu, 8 tahun yang lalu. Ketika usiaku 10 tahun.
Aku akan bermain sampai bedug maghrib bergema dari masjid di
dekat rumahku. Sampai mama berteriak dari depan gang untuk menyuruhku segera
pulang dan berbuka puasa. Sampai teman-temanku yang lain berhamburan menuju
rumahnya masing-masing. Lalu aku pun segera berlari pulang dan menyerbu meja
makan mencari es buah atau kolak pisang buatan mama.
Saat ini aku hanya menjadi penonton. Menyaksikan kehidupan
selain kehidupanku. Pada bulan Ramadhan setiap tahunnya, seminggu sekali aku
akan datang ke lapangan ini. Mengenang cerita masa kecilku yang penuh dengan
keceriaan.
Begitu bedug maghrib bergema, aku berlari menuju rumahku.
Membuka tajil yang aku beli tadi di jalan dan memakannya di depan rumah yang menyisakan
puing-puing kebakaran 7 tahun lalu. Kebakaran yang menghabiskan seluruh isi rumahku
dan membuatku berpisah dengan mama
selamanya.
Bukan! Aku tidak sedang meratapi kesedihan. Aku hanya ingin
mengenang. Toh untuk apa terus bersedih? Kesedihan tak membuatku bertemu mama. Kesedihan
tak membuat rumahku kembali seperti semula. Kesedihan hanya membuatku jatuh
lebih dalam.
Kata Tak Terucap
Aku datang bukan untuk mengucapkan kata yang selalu
terngiang di kepalaku. Kata yang seharusnya ada untuk mengungkapkan penyesalan.
Kata yang selalu mendesak untuk keluar dari mulutku. Tapi mulutku sendiri
terlalu kuat menahannya, mengekang kata itu untuk tak muncul di permukaan. Dan
hatiku menyetujuinya.
Aku ingat saat orangtuamu datang menjemputmu. Mencoba
menarikmu, membawamu jauh dariku. Padahal sudah susah payah aku menjauhkanmu
dari kungkungan orangtuamu. Membawamu, itu adalah permintaanmu.
Kamu meronta, meminta orangtuamu membebaskanmu untuk
menentukan pilihan, yaitu AKU. Tetapi mereka seolah tak peduli. Aku tak baik
bagimu, begitu pikir mereka. Sudah ada laki-laki baik menurut mereka yang
diperuntukkan menjadi pasanganmu.
Tentu saja aku tak akan membiarkan. Aku mencintaimu. Kamu
pun begitu. Tak bisakah mereka mengerti?
Sekarang, setelah sekian lama, aku kembali menemuimu. Tak
ada penyesalan mengapa aku masih mencintaimu. Walaupun hidupku sengsara karena hal itu. 10
tahun atau mungkin lebih. Aku tak menghitungnya.
Jika aku tak bisa memilikimu, orang lain juga tak boleh
memilikimu. Meskipun itu orangtuamu, apalagi laki-laki yang tak kutahu.
Bukan, bukan kepanikan atau keterpaksaan Lala. Aku tak
menyesal melakukannya saat itu. Aku percaya, kamu juga menginginkannya. Pergi meninggalkan
kita semua, membebaskanmu, mungkin memang itu hal yang sebaiknya.
Yang terpenting, senyum manismu, sorot mata manjamu, derai
tawamu, pelukan hangatmu, hanya untukku. Bahkan sampai saat terakhirmu, aku lah
yang kamu lihat. Menemanimu menutup mata.
Aku berjanji akan selalu mengunjungimu. Membawakan bunga
kesukaanmu. Menceritakan kisah-kisah kita dulu. Walaupun ku tahu kamu tak bisa
lagi memberi respon atas apa yang kulakukan untukmu.
Tetap saja kata itu tak bisa terucap Lala...